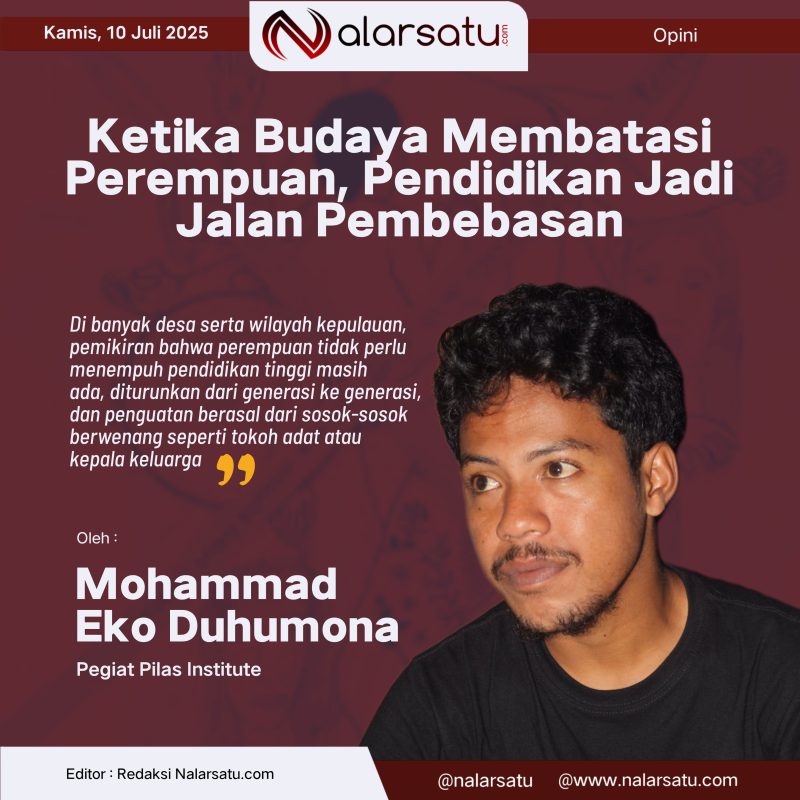Oleh: Mohammad Eko Duhumona – Pegiat Pilas Institute
DI balik pertumbuhan pembangunan dan kemajuan teknologi yang terus-menerus dipromosikan, masih ada banyak gadis di daerah terpencil dalam negeri ini yang terpaksa menguburkan harapan mereka hanya karena mereka perempuan. Di beberapa wilayah, termasuk daerah kepulauan, norma dan tradisi yang sudah mengakar memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat tentang perempuan. Perempuan yang menempuh pendidikan tinggi sering kali dianggap melampaui batas kodrat. Mereka yang memilih untuk menunda pernikahan demi melanjutkan studi justru dipersepsikan sebagai penantang nilai-nilai budaya. Ini bukan sekadar masalah pola pikir kuno, tetapi juga ketidakadilan sistemik yang dibiarkan berlanjut dalam masyarakat.
Kesenjangan ini semakin mencolok di daerah pedesaan. Berdasarkan data BPS 2022, persentase perempuan yang lulus dari perguruan tinggi di perkotaan adalah 13,97%, lebih dari dua kali lipat dibandingkan di pedesaan yang hanya 6,00% . Selain itu, terdapat 7,35% perempuan usia 15 tahun ke atas di pedesaan yang buta huruf, sementara di perkotaan hanya 2,83% .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbedaan pendidikan antara pria dan wanita di Indonesia bukan hanya hasil dari kebetulan, melainkan akibat dari struktur sosial dan kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan secara tegas hanya diberikan kepada kalangan bangsawan dan laki-laki. Perempuan diposisikan sebagai pengurus rumah tangga dan tidak dipandang perlu untuk mendapatkan akses pada ilmu pengetahuan secara sejajar. Bahkan dalam sistem pendidikan awal Belanda, lembaga-lembaga seperti Hollandsch-Inlandsche School atau Europeesche Lagere School menutup akses bagi mayoritas perempuan lokal.
Tokoh seperti Raden Ajeng Kartini bukan hanya lambang perjuangan perempuan, tetapi juga bukti nyata betapa sulitnya perjuangan untuk sekadar mendapat pendidikan. Dalam surat-suratnya, Kartini mencatat bagaimana budaya Jawa yang sangat patriarkal melarang perempuan dari kalangan bangsawan untuk keluar rumah setelah mencapai usia dewasa. Ketika ia memperjuangkan pendidikan untuk perempuan melalui Sekolah Kartini, itu bukan sekadari inovasi dalam dunia pendidikan—itu adalah tindakan perlawanan terhadap sistem sosial yang menganggap perempuan sebagai barang milik keluarga.
Sayangnya, semangat seperti itu belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan yang kita jalankan saat ini. Meskipun Undang-Undang Dasar dan berbagai kebijakan pendidikan memastikan hak setiap warga negara, praktik sosial dan budaya yang bersifat diskriminatif masih tetap ada dengan alasan “adat” atau “tradisi“. Di banyak desa serta wilayah kepulauan, pemikiran bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi masih ada, diturunkan dari generasi ke generasi, dan penguatan berasal dari sosok-sosok berwenang seperti tokoh adat atau kepala keluarga.
Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk pendidikan perempuan bukan hanya berhenti pada penyediaan sarana dan kebijakan, tetapi juga tentang menghapus warisan sejarah yang sudah lama menindas dan mematikan suara perempuan atas nama budaya serta norma lokal. Bahkan sampai sekarang, pertikaian antara kemodernan pendidikan dan pelestarian budaya sering kali dimenangkan oleh pandangan konservatif—dan yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan yang kehilangan peluang di masa depan.
Secara yuridis, hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan sudah dijamin melalui berbagai peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi. Lebih dari itu, ratifikasi CEDAW (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) oleh Indonesia memberikan landasan bagi komitmen negara untuk menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Perempuan memainkan peran penting di sektor pendidikan. Namun, dalam prakteknya, kondisinya masih jauh dari harapan. Kebijakan yang ada seringkali tidak mencerminkan keadaan sosial yang sebenarnya. Sebagai contoh, intervensi tegas dari pemerintah daerah terhadap pernikahan dini atau larangan bagi perempuan hamil untuk bersekolah masih sangat terbatas—kedua isu ini seringkali menjadi penghalang bagi pendidikan perempuan di wilayah tertentu.
Perempuan bukan hanya objek yang perlu “diberdayakan. ” Mereka merupakan agen yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan sosial yang signifikan dalam komunitas. Perempuan yang berpendidikan mampu menciptakan keluarga yang sehat, meningkatkan kestabilan ekonomi rumah tangga, dan memberikan pola pikir yang lebih terbuka kepada anak-anak. Bahkan, UNESCO mencatat bahwa penambahan satu tahun pendidikan untuk perempuan dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 20%. Namun, di sisi lain, tekanan sosial, norma-norma tradisional, dan stigma terhadap perempuan yang dianggap “terlalu bebas” masih menjadi penghalang. Di banyak komunitas, perempuan yang memiliki pemikiran kritis dan mandiri sering kali dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk tidak bersuara, tunduk, dan melepaskan hak-hak mereka demi menjaga apa yang mereka anggap sebagai “kestabilan sosial” yang semu.
Pendidikan merupakan proses pembebasan. Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan yang sejati berfungsi untuk membebaskan dari berbagai bentuk penindasan—baik yang berbentuk struktural maupun kultural. Ini berarti bahwa perempuan tidak hanya harus belajar membaca dan berhitung, tetapi juga memahami bahwa mereka memiliki hak, potensi, dan suara dalam masyarakat. Banyak yang masih memandang pendidikan bagi perempuan sebagai sesuatu yang tambahan dan bukan sebagai kebutuhan utama. Padahal, negara yang ingin berkembang harus menyadari bahwa pendidikan untuk perempuan adalah suatu investasi jangka panjang dan bukan suatu beban. Masyarakat yang terus memandang perempuan sebagai golongan kelas dua hanya berdasarkan jenis kelamin mereka, sedang menciptakan ketidakadilan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Jika saat ini kita masih menyaksikan anak-anak perempuan di desa menikah sebelum menyelesaikan pendidikan SMP, atau jika kita masih mendengar orang tua berkata “tidak ada gunanya sekolah tinggi jika ujungnya di dapur”, maka kita sedang menghadapi keadaan darurat sosial yang tidak bisa dibiarkan lagi. Pendidikan adalah cara yang paling logis dan strategis untuk membebaskan perempuan dari hambatan budaya, kemiskinan, dan ketidakadilan. Namun, pendidikan tersebut harus dijamin, dilindungi, dan diperjuangkan—oleh negara, oleh masyarakat, dan oleh kita semua. (*)