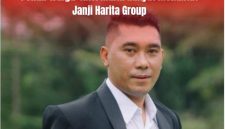Oleh: Riski Ikra –Mahasiswa Perikanan Ummu
“Yang rutin itu bukan kuliah, tapi kekecewaan. Karena dosen datang cuma pas ujian, semester.”
KAMPUS selama ini dipandang sebagai ruang suci di mana ilmu pengetahuan berkembang, tempat di mana intelektualitas dibentuk, dan nalar kritis diasah. Namun, realitas yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi, khususnya di Maluku Utara, mengingatkan kita bahwa ruang suci ini kini sedang mengalami krisis yang mendalam. Krisis yang tidak hanya soal kualitas kurikulum atau fasilitas, tapi lebih pada hilangnya sosok sentral yang seharusnya menjadi nadi hidup kampus: dosen. Fenomena yang kini marak terjadi dan sering disebut “dosen siluman” yakni dosen yang secara administratif ada, menerima gaji atau honorarium, tapi nyaris tak pernah mengajar secara nyata adalah cerminan dari kegagalan sistemik yang lebih besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bayangkan, sebagai mahasiswa, Anda mengharapkan bimbingan, arahan, dan interaksi langsung yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan kemampuan kritis. Namun yang terjadi adalah kehadiran dosen sebatas formalitas, di mana kuliah berubah menjadi tugas mandiri tanpa arahan, kelas diskusi yang kosong, atau komunikasi yang hanya sebatas pesan WhatsApp. Rasa kecewa bukan hanya karena materi yang sulit, tapi juga karena kehadiran sosok pengajar yang semestinya menjadi jembatan antara teori dan praktik hampir tidak ada.
Mengapa hal ini terjadi? Untuk menjawabnya, kita harus merenungi makna kehadiran dosen itu sendiri. Dalam tradisi keilmuan klasik, guru atau dosen bukan hanya sekadar pengajar. Dalam tradisi Islam, Al-Ghazali menggambarkan guru sebagai pewaris tugas kenabian yang tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga membentuk akhlak dan kesadaran. Sementara di dunia Barat, Socrates berdiri sebagai lambang guru yang hadir bukan untuk mengajar secara formal, tetapi untuk membimbing nalar melalui dialog dan debat langsung di ruang publik. Guru-guru tersebut hidup dan bekerja dengan penuh dedikasi, bukan demi materi semata, tapi untuk membentuk generasi penerus yang kritis dan berintegritas.
Kini, kehadiran dosen yang semestinya menjadi motor penggerak proses belajar justru kian menghilang. Kehadiran fisik di kelas sering kali diganti dengan metode pengajaran yang minim interaksi dan inovasi, bahkan kadang hanya sekadar mengisi presensi. Sistem yang sudah birokratis ini membuat dosen tidak lagi dipandang sebagai figur intelektual yang berperan aktif, melainkan lebih sebagai pegawai yang menjalankan tugas administratif. Hal ini tentu sangat menyedihkan, karena yang dirugikan bukan hanya mahasiswa, tapi masa depan bangsa yang membutuhkan pemikir-pemikir kritis dan inovatif.
Fenomena dosen siluman tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan di dalam sistem kampus yang kental dengan budaya feodal dan patronase. Jabatan dan kedekatan personal sering lebih menentukan daripada kualitas pengajaran dan kontribusi akademik. Di kampus-kampus besar seperti UMMU dan Unkhair di Maluku Utara, tidak sedikit dosen yang lebih mengutamakan jabatan birokrasi, proyek luar kampus, atau kegiatan lain yang jauh dari tugas utamanya sebagai pendidik. Akibatnya, kampus berubah menjadi arena persaingan kekuasaan dan keuntungan, bukan lagi pusat pencerdasan dan pembentukan karakter.
Max Weber pernah menjelaskan bagaimana birokrasi tanpa nilai melahirkan “mekanisme kosong” yang berjalan secara formal tanpa substansi. Hal ini sangat relevan dengan kondisi kampus saat ini, di mana sistem berjalan sesuai aturan, namun substansi pengajaran dan pembelajaran menjadi hampa. Paulo Freire bahkan lebih tegas mengatakan bahwa sistem seperti ini merupakan bentuk penindasan epistemik, di mana mahasiswa menjadi objek pasif, kehilangan peran aktifnya sebagai subjek dalam proses pengetahuan. Dengan kata lain, mahasiswa bukan lagi mitra dalam pembelajaran, melainkan konsumen pasif yang menerima apa adanya.
Sebagai mahasiswa, mungkin Anda pernah merasa kecewa, bahkan frustasi, menghadapi situasi ini. Tapi apakah kita cukup diam saja? Budaya diam dan pasif ini justru menjadi salah satu penyebab memburuknya kualitas pendidikan. Di kampus-kampus Maluku Utara, keluhan mahasiswa sering kali hanya jadi bahan omongan santai di warung kopi atau guyonan di media sosial, tanpa berani menyuarakan secara langsung kepada pihak kampus. Rasa takut, apatisme, dan ketakutan akan konsekuensi akademik membuat mahasiswa lebih memilih diam, demi kelulusan cepat dan aman dari konflik.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa pernah menjadi agen perubahan yang kritis dan berani menentang ketidakadilan. Namun hari ini, di tengah ketidakhadiran dosen dan minimnya ruang dialog yang sehat, mahasiswa justru menyusut perannya. Kampus yang seharusnya menjadi tempat kebebasan berpikir dan ekspresi berubah menjadi ruang ketakutan dan pengekangan. Nilai-nilai akademik yang luhur digantikan oleh pragmatisme dan ketidakpedulian.
Melihat kondisi kampus hari ini, tampak bahwa kehadiran dosen yang konsisten dalam proses belajar mengajar semakin menjadi masalah serius. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa bahwa dosen mereka jarang hadir secara penuh selama satu semester, sebuah realitas yang bukan sekadar angka statistik kecil, melainkan sebuah peringatan keras akan krisis pendidikan. Sayangnya, sistem evaluasi dan penegakan disiplin terhadap dosen yang abai terhadap tanggung jawabnya masih berjalan lemah dan minim transparansi.
Maka dari itu, reformasi akademik bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Mahasiswa harus dilibatkan secara aktif dalam evaluasi kinerja dosen, bukan hanya sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai mitra yang berhak menyuarakan aspirasi dan kritik. Lembaga-lembaga independen mahasiswa perlu diberdayakan untuk menjadi kontrol sosial yang efektif. Kampus harus membuka ruang dialog terbuka dan transparan antara dosen, mahasiswa, dan pimpinan agar semua pihak dapat bertanggung jawab dan berkontribusi secara nyata.
Kampus boleh megah dengan gedung-gedung megah dan fasilitas lengkap, tapi tanpa dosen yang hadir secara sungguh-sungguh mengajar dan membimbing, maka semua itu hanyalah kulit kosong. “Dosen siluman” adalah manifestasi dari penyakit sistemik berupa pembiaran dan kematian nalar kritis. Jika kampus di Maluku Utara ingin benar-benar menjadi pusat keilmuan dan pengembangan karakter, maka bukan gedung yang harus dibangun terlebih dahulu, melainkan etika dan tanggung jawab intelektual yang harus ditegakkan secara konsisten.
Sebagai mahasiswa, posisi Anda bukan hanya sebagai penerima ilmu, tetapi juga sebagai penjaga ruang akademik. Jangan biarkan suara dan peran kritis Anda hilang oleh keheningan yang dipaksakan. Kampus bukan mesin cetak gelar, melainkan tempat di mana akal sehat dan nurani ditumbuhkan. Dan di tempat itu, tidak boleh ada yang menjadi “siluman.” Saatnya bangkit, sadar, dan menuntut perubahan demi masa depan pendidikan yang lebih baik. “Selama yang hadir hanya bayangan, jangan heran jika hasilnya hanyalah ilusi pengetahuan.” (*)