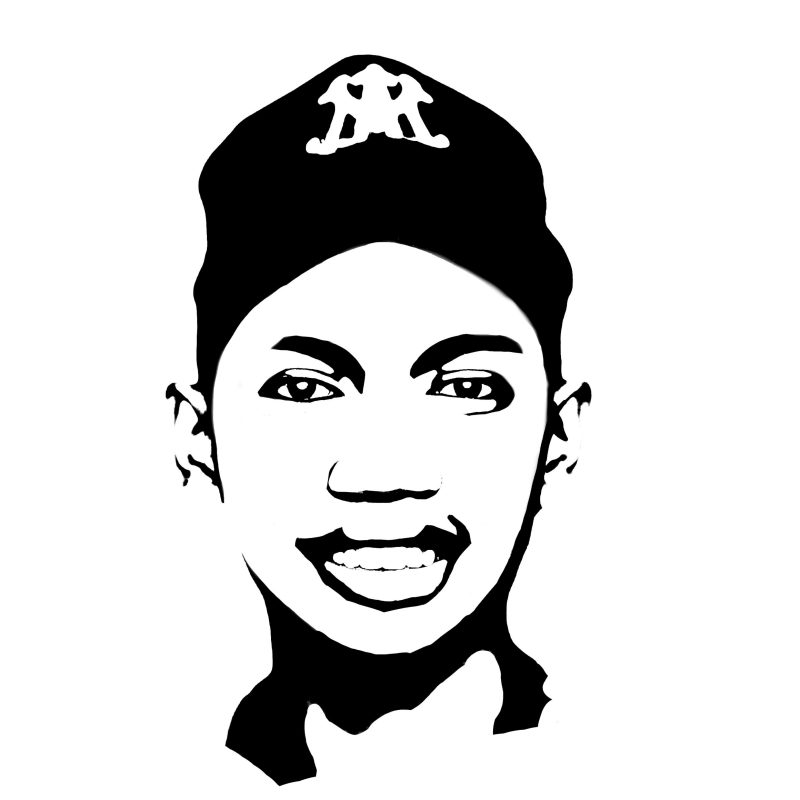Oleh: Dahril Fardinan* – CA Forum Insan Cendikia (FIC) dan Mahasiswa PWK Unutara
SECARA umum, dalam pandangan Karl Marx, pertambangan sebagai bagian dari sistem kapitalis tidak terlepas dari kritik terhadap eksploitasi dan alienasi. Marx melihat pertambangan sebagai industri yang mengeksploitasi tenaga kerja manusia dan sumber daya alam demi keuntungan para pemilik modal yang dikenal sebagai kaum kapitalis. Dalam sistem kapitalisme, kekayaan hanya terakumulasi pada segelintir elit ekonomi, sedangkan pekerja tambang yang menjadi penggerak utama produksi justru mengalami penindasan dan keterasingan. Mereka kehilangan kontrol atas hasil kerjanya sendiri, teralienasi dari lingkungan tempat mereka hidup, dan hanya menjadi roda kecil dari mesin besar kapitalisme.
Namun dalam pandangan Aristoteles, pertambangan bukanlah aktivitas ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekonomi rumah tangga dan negara yang lebih luas. Aristoteles menekankan pentingnya pengolahan sumber daya alam, termasuk logam dan mineral, untuk kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dalam pemikiran klasiknya, kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan berkeadilan dalam masyarakat. Pertambangan, menurutnya, harus dijalankan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan manfaat bagi seluruh warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akan tetapi, jika kita menilik kondisi pertambangan yang terjadi di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Timur, maka realitasnya sangat jauh dari pemikiran Aristoteles dan justru lebih mirip dengan kritik tajam Karl Marx. Pertambangan yang semestinya menjadi pendorong kemakmuran, kini justru menjadi ladang perampasan dan sumber petaka bagi masyarakat. Realita yang kini kita lihat menunjukkan begitu banyaknya masalah yang muncul di dalam lingkup sektor pertambangan, mulai dari perampasan hak-hak masyarakat, kerusakan lingkungan, pencemaran air, hingga lemahnya perlindungan hukum dari pemerintah daerah.
Pertambangan di Halmahera Timur telah menyebabkan perubahan signifikan pada tata guna lahan. Wilayah yang sebelumnya berupa hutan lindung, kebun masyarakat, dan tanah adat, kini berubah menjadi kawasan tambang terbuka dan infrastruktur industri. Operasi pertambangan dan konstruksi jalan tambang telah menyebabkan deforestasi besar-besaran, hilangnya biodiversitas, serta rusaknya sistem ekologi yang selama ini menopang kehidupan masyarakat lokal. Bahkan di beberapa daerah, masyarakat tidak lagi memiliki akses ke lahan yang secara turun-temurun mereka kelola, karena tanah-tanah tersebut telah masuk ke dalam konsesi pertambangan tanpa musyawarah dan tanpa proses ganti rugi yang adil.
Pencemaran air menjadi salah satu dampak lingkungan paling nyata yang dirasakan oleh warga. Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber air bersih dan tempat aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memancing, kini berubah warna menjadi kecoklatan, keruh, dan tidak layak digunakan. Limbah tambang yang tidak diolah dengan baik mengalir bebas ke badan air, menyebabkan pencemaran logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Banyak warga yang mengeluh terkena penyakit kulit, iritasi, dan gangguan pencernaan karena terpaksa menggunakan air tercemar. Sayangnya, perusahaan tambang acapkali mengelak dari tanggung jawab, bahkan memanipulasi data lingkungan untuk menghindari sanksi hukum.
Yang lebih menyedihkan adalah sikap pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang seolah-olah menutup mata terhadap berbagai pelanggaran ini. Pemprov dan DPRD hanya diam di tempat, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Alih-alih membela rakyat yang menjadi korban, mereka justru sibuk membangun kemitraan dengan para pemilik modal tambang. Elite politik di Maluku Utara terlihat lebih mementingkan kedekatan dengan pemodal demi keuntungan jangka pendek daripada keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan. Mereka duduk di kursi kekuasaan, tetapi tidak lagi menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap rakyat. Padahal, jabatan yang mereka emban seharusnya menjadi alat perjuangan untuk kepentingan publik, bukan menjadi jembatan transaksi dengan kapitalis.
DPRD yang diharapkan menjadi suara rakyat justru terlihat lumpuh dalam menyikapi dampak pertambangan. Wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu demokratis, ternyata lebih senang diam daripada bersuara. Pertanyaannya kemudian, buat apa kita memilih wakil rakyat jika mereka justru abai terhadap hak-hak konstituennya. Hak masyarakat diambil, lingkungan dirusak, dan air tercemar, tetapi tidak ada satupun anggota dewan yang berani menyatakan sikap kritis terhadap perusahaan.
Sektor pertambangan yang ada di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Timur, ternyata bukan untuk mensejahterakan masyarakat. Justru sebaliknya, tambang membawa dampak buruk yang sangat serius. Bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga tatanan sosial yang terganggu. Masuknya perusahaan besar ke wilayah-wilayah desa menyebabkan perpecahan antarwarga, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, serta terganggunya kearifan lokal yang selama ini hidup harmonis dengan alam. Pemerintah pusat pun tampaknya tidak memiliki kepekaan terhadap situasi yang dihadapi masyarakat di wilayah timur. Mereka terlalu sibuk mengurus proyek strategis nasional, tanpa melihat langsung dampak kerusakan ekologis yang dialami masyarakat pelosok.
Kondisi ini memperjelas bahwa pertambangan yang berjalan saat ini bukanlah pertambangan yang berkeadilan. Ia tidak lahir dari dialog dengan rakyat, tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran atas nama investasi, yang menyisakan luka dan penderitaan berkepanjangan. Keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara mayoritas rakyat Maluku Utara hanya bisa melongo melihat air yang berubah warna, udara yang penuh debu, dan lahan yang tak lagi mereka kuasai.
Penulis meyakini bahwa selama pemerintah daerah dan DPRD masih sibuk menjalin kemitraan dengan kaum kapitalis, maka penderitaan masyarakat tidak akan pernah berakhir. Seharusnya para pemimpin daerah berhenti menjadi perpanjangan tangan korporasi dan kembali berpihak pada rakyat. Mereka harus berani mengatakan tidak terhadap tambang-tambang yang merusak, dan memprioritaskan keselamatan lingkungan serta hak-hak warga lokal. Jika pemerintah daerah tidak sanggup menertibkan perusahaan tambang, maka sudah sepatutnya pemerintah pusat turun tangan dan mencabut seluruh izin operasi yang terbukti merugikan rakyat.
Pertambangan seharusnya menjadi jalan bagi kemajuan, bukan alasan untuk memperkaya segelintir elit. Ia harus dikelola secara adil, transparan, dan partisipatif. Rakyat harus diberikan posisi sebagai subjek, bukan hanya objek penderita. Pengetahuan lokal harus dihargai, bukan dikorbankan demi logika pasar global. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka Maluku Utara akan kehilangan masa depannya, alam yang rusak, masyarakat yang kehilangan tanah dan air, serta generasi muda yang tumbuh dalam keterasingan ekologis dan sosial.
Dengan itu, penulis menyarankan bahwa untuk mengurangi dampak buruk pertambangan terhadap masyarakat, maka perlu ada langkah tegas dan menyeluruh dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat sipil. DPRD dan Pemprov harus berhenti menjadi kaki tangan kapitalis, dan mulai membela rakyat yang terdampak. Pemerintah pusat harus membuka mata terhadap situasi di timur Indonesia, dan segera mencabut surat izin operasi pertambangan yang terbukti menimbulkan kerusakan. Hutan-hutan di Halmahera Timur harus dilindungi, bukan dikorbankan demi laba.
Masyarakat Maluku Utara berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan lestari. Mereka bukan sekadar penonton atas nasib sendiri. Dan negeri ini tidak akan pernah benar-benar merdeka, jika rakyat di timur masih terus ditindas oleh sistem yang mengagungkan kapital dan mengabaikan keadilan. (*)