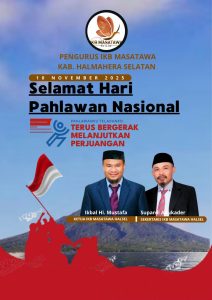Oleh: Asmar Hi. Daud – Mahasiswa Doktoral Ilmu Kelautan (IK) Unsrat Manado
PULAU Obi hari ini adalah cermin paling terang dari konflik pembangunan di Maluku Utara. Di tengah gegap-gempita operasi raksasa industri nikel, warga Desa Kawasi justru hidup dalam lingkaran krisis: listrik mati-hidup, air bersih langka, dan layanan dasar yang tak pernah hadir secara layak. Ironisnya, ketika tungku smelter perusahaan menyala tanpa henti dan kapal kargo lalu-lalang mengantar bijih ke pasar global, kampung di ring-satu tambang justru tenggelam dalam gelap dan kekeringan.
Harita Group selama ini mengklaim menyediakan listrik dan air bagi masyarakat melalui program CSR. Namun fakta lapangan berbicara lain. Warga masih harus membeli air, listrik tidak stabil, dan instalasi yang diklaim dibangun perusahaan tidak menghadirkan manfaat nyata. Jika fasilitas itu memang ada, mengapa tidak bekerja? Jika akses itu tersedia, mengapa warga tidak merasakannya?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi yang tidak wajar ini memunculkan dugaan lain: krisis listrik dan air diduga berkaitan dengan rencana relokasi Desa Kawasi. Berbagai warga menyatakan, layanan dasar terus memburuk sementara tawaran pindah ke “pemukiman baru” semakin gencar. Jika dugaan ini benar, maka persoalan Kawasi bukan lagi sekadar kerusakan jaringan atau ketidaksiapan teknis, melainkan menyentuh ranah hak dasar warga dan potensi praktik pemiskinan struktural.
Dari perspektif sosial-ekologis, situasi di Obi memperlihatkan gambaran klasik ketimpangan tata kelola. Industri memperoleh kendali penuh atas ruang, energi, dan fasilitas, sedangkan masyarakat justru menanggung risiko terbesar—mulai dari pencemaran, kehilangan sumber hidup, hingga layanan dasar yang tidak pernah setara. Ini adalah bentuk pertukaran yang tidak adil (unequal exchange): keuntungan mengalir ke pusat industri dan modal, sementara beban sosial-ekologis menumpuk di pundak masyarakat pesisir sebuah pulau kecil.
Dalam logika keadilan lingkungan, listrik dan air bersih bukan hadiah CSR, tetapi hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dan perusahaan. Jika industri mampu menyalakan smelter 24 jam sehari, maka mustahil kampung yang hanya berjarak beberapa kilometer hidup dalam kegelapan. Ini bukan masalah teknis. Ini masalah keberpihakan.
Tulisan ini bukan ajakan menolak industri. Ini adalah teriakan atas ketidakadilan yang terus berlangsung di Kawasi. Kehadiran industri seharusnya meningkatkan kualitas hidup, bukan mengikis hak-hak paling mendasar masyarakat. Pemerintah daerah wajib melakukan audit independen terhadap layanan listrik dan air, membuka data distribusi energi, mengevaluasi izin, dan memastikan perusahaan memenuhi kewajiban sosialnya secara substansial, bukan seremonial.
Pada titik ini, apa yang terjadi di Obi menunjukkan bahwa kemajuan yang membakar kampung di sekelilingnya bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang dibungkus kilau nikel. Pulau kecil seperti Obi tidak boleh menjadi korban ambisi industri. Warga Kawasi berhak hidup terang, berhak atas air bersih, dan berhak atas martabat di tanah mereka sendiri.