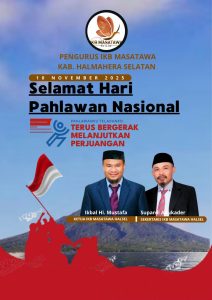Oleh: Okte Histori – Pegiat Literasi dan Aksi Jalanan.
KONFLIK agraria antara korporasi dan masyarakat adat atau pemilik lahan bukanlah fenomena baru di Indonesia. Namun, setiap kasus yang mencuat ke permukaan publik selalu membawa cerita yang sama: ketimpangan kuasa, proses yang tidak transparan, dan masyarakat yang menjadi korban. Kasus terbaru di Halmahera Selatan, Maluku Utara, antara ahli waris pemilik lahan dengan PT Harita Nickel, kembali mengulangi pola lama yang tak kunjung terselesaikan dalam tata Kelola pertambangan dan Pembangunan di Indonesia.
Insiden saling dorong antara pemilik lahan dan petugas keamanan perusahaan bukanlah sekadar gesekan fisik biasa. Ia adalah simbol dari frustrasi yang telah lama terpendam, ketidakadilan yang terakumulasi, dan ketidakberdayaan masyarakat menghadapi mesin kapitalisasi sumber daya alam yang beroperasi dengan dukungan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Aksi pemalangan yang dilakukan ahli waris adalah bentuk perlawanan terakhir Ketika semua jalur komunikasi dan mediasi tampak tertutup atau diabaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kronologi kasus ini mengungkap pola yang kerap terjadi dalam konflik lahan di Indonesia: apa yang awalnya dikomunikasikan sebagai kegiatan kecil dan sementara, kemudian berubah menjadi proyek permanen berskala besar tanpa persetujuan yang memadai. Pada 2023, PT Harita Nickel meminta izin untuk melakukan pengambilan sampel atau pengeboran di beberapa titik kebun milik warga. Permintaan yang terdengar teknis dan terbatas ini kemungkinan besar disetujui oleh pemilik lahan dengan asumsi bahwa kegiatan tersebut bersifat sementara dan tidak akan mengubah status atau fungsi lahan mereka.
Namun pada tahun 2025, tanpa pemberitahuan yang jelas atau negosiasi ulang, proyek besar pembangunan bendungan dimulai di lokasi yang sama. Perubahan drastis dari kegiatan eksplorasi menjadi konstruksi infrastruktur besar ini menunjukkan ada yang salah dalam proses komunikasi dan perizinan. Apakah sejak awal perusahaan sudah merencanakan pembangunan bendungan namun sengaja tidak mengungkapkannya? Atau apakah hasil eksplorasi kemudian memunculkan rencana baru yang tidak dikomunikasikan kepada pemilik lahan? Apapun jawabannya, ketiadaan transparansi dan kejujuran dalam komunikasi telah menciptakan konflik yang bisa dihindari.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah klaim perusahaan bahwa mereka telah membayar lahan tersebut kepada pihak tertentu, namun menolak mengungkapkan identitas penerima pembayaran dengan alasan “rahasia”. Dalam konteks hukum pertanahan Indonesia, kerahasiaan semacam ini sangat mencurigakan. Transaksi tanah adalah urusan hukum yang harus melibatkan pemilik sah, saksi-saksi, dan idealnya disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika transaksi dilakukan secara legal dan sah, tidak ada alasan untuk merahasiakan identitas pihak yang terlibat, terutama ketika ahli waris yang sah mempertanyakannya.
Dugaan adanya mafia tanah dalam kasus ini bukanlah tuduhan kosong. Mafia tanah adalah realitas yang sudah lama beroperasi di Indonesia, memanfaatkan celah-celah hukum, dokumen palsu, atau kolusi dengan pihak berwenang untuk mengklaim kepemilikan lahan yang bukan haknya. Modus operandi mereka bervariasi: ada yang menggunakan surat palsu, ada yang memanfaatkan ketidaktahuan pemilik lahan tentang prosedur hukum, ada pula yang berkolaborasi dengan oknum pemerintah untuk memalsukan dokumen kepemilikan.
Dalam kasus PT Harita Nickel, informasi bahwa proses penjualan lahan dilakukan tanpa menghadirkan ahli waris asli adalah indikasi kuat adanya praktik ilegal. Dalam hukum waris Indonesia, baik berdasarkan hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam, ahli waris memiliki hak yang jelas dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Transaksi yang melibatkan tanah warisan harusnya melibatkan semua ahli waris atau setidaknya mendapat persetujuan mereka. Jika hal ini tidak terjadi, maka transaksi tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan.
Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah fakta bahwa perusahaan besar seperti PT Harita Nickel seharusnya memiliki tim legal yang kompeten untuk melakukan due diligence terhadap setiap transaksi lahan. Mereka seharusnya memeriksa sertifikat tanah, melakukan pengecekan silang dengan data Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan memastikan bahwa pihak yang mengklaim sebagai pemilik benar-benar adalah pemilik yang sah. Jika perusahaan gagal melakukan ini, ada dua kemungkinan: pertama, mereka lalai dan tidak profesional. kedua, mereka tahu ada masalah tetapi memilih untuk mengabaikannya karena berbagai kepentingan.
Kemungkinan ketiga, yang paling mengkhawatirkan, adalah bahwa perusahaan justru terlibat atau setidaknya membiarkan praktik mafia tanah ini terjadi karena lebih mudah dan murah berurusan dengan “pemilik palsu” daripada bernegosiasi dengan ahli waris yang sah. Praktik seperti ini, jika benar terjadi, adalah kejahatan yang merugikan tidak hanya individu pemilik lahan, tetapi juga integritas sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap korporasi.
Kasus ini juga menyingkap dimensi ketidakadilan struktural yang lebih luas dalam relasi antara korporasi, negara, dan masyarakat. Proyek bendungan yang dibangun oleh PT Harita Nickel kemungkinan besar adalah bagian dari infrastruktur penunjang operasi tambang nikel mereka. Nikel adalah komoditas strategis, terutama dalam era transisi energi global di mana permintaan terhadap baterai kendaraan listrik melonjak drastis. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar didun ia, menjadi incaran investasi besar-besaran dari berbagai negara dan korporasi multinasional.
Dalam konteks kepentingan ekonomi dan geopolitik yang besar ini, hak-hak masyarakat lokal sering kali dipandang sebagai “hambatan” yang harus “dikelola” atau bahkan dihilangkan. Narasi pembangunan dan kemajuan ekonomi kerap digunakan untuk melegitimasi pengabaian terhadap hak-hak dasar masyarakat atas tanah, lingkungan, dan penghidupan mereka. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali lebih berpihak pada kepentingan investor dengan argumen bahwa investasi akan membawa lapangan kerja, pajak, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun kenyataannya, manfaat ekonomi dari proyek-proyek besar seperti ini jarang sekali dinikmati secara adil oleh masyarakat lokal. Yang mereka rasakan justru dampak negatif: kehilangan tanah, kerusakan lingkungan, polusi air dan udara, perubahan sosial-budaya, dan marginalisasi ekonomi. Sementara keuntungan besar mengalir ke perusahaan dan pemegang saham yang Sebagian besar berada di luar daerah bahkan di luar negeri.
Salah satu masalah mendasar dalam kasus ini adalah ketiadaan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan mengklaim telah membayar lahan, tetapi menolak memberikan bukti atau mengungkapkan kepada siapa pembayaran dilakukan. Ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam negara hukum. Transparansi bukan hanya soal etika bisnis, tetapi juga prinsip fundamental dalam tata Kelola yang baik (good governance).
Dalam konteks pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur atau pertambangan, seharusnya ada mekanisme yang jelas dan terbuka. Semua transaksi harus didokumentasikan dengan baik, melibatkan pihak-pihak yang berwenang seperti BPN, notaris, dan pemerintah daerah. Masyarakat yang terkena dampak harus dilibatkan sejak awal melalui proses konsultasi publik yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Mereka harus mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang proyek, dampaknya, dan hak-hak mereka.
Sayangnya, dalam banyak kasus, proses semacam ini lebih merupakan pengecualian daripada aturan. Perusahaan dan pemerintah sering kali melakukan apa yang disebut sebagai “konsultasi publik” yang sebenarnya hanya sosialisasi sepihak tanpa memberi ruang bagi keberatan atau negosiasi substansial. Dokumen-dokumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sering kali sulit diakses oleh masyarakat. Informasi tentang kompensasi dan Ganti rugi tidak dijelaskan secara detail dan adil.
Ketiadaan transparansi ini menciptakan ruang bagi berbagai praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mafia tanah bisa beroperasi karena prosesnya tidak transparan. Oknum pemerintah bisa menerima suap karena tidak ada pengawasan yang efektif. Perusahaan bisa melakukan pelanggaran karena tidak ada akuntabilitas yang nyata.
Dalam konflik agraria seperti ini, peran negara seringkali ambigu atau bahkan cenderung berpihak pada korporasi. Ini adalah ironi mengingat konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip konstitusional ini seharusnya menempatkan negara sebagai pelindung kepentingan rakyat, bukan sebagai fasilitator kepentingan korporasi yang sering kali bertentangan dengan kepentingan Masyarakat lokal.
Namun dalam praktiknya, negara sering kali lebih berperan sebagai “makelar” yang memfasilitasi masuknya investasi dengan berbagai kemudahan, termasuk mempercepat perizinan dan “menyelesaikan” masalah tanah dengan cara-cara yang merugikan masyarakat. Aparatur keamanan, baik polisi maupun TNI, kerap dikerahkan bukan untuk melindungi hak-hak masyarakat, tetapi untuk mengamankan proyek perusahaan dan meredam protes masyarakat.
Dalam kasus PT Harita Nickel, kehadiran sekuriti perusahaan yang terlibat insiden saling dorong dengan warga adalah bentuk “privatisasi keamanan” yang problematis. Sekuriti swasta tidak memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan represif terhadap warga negara. Jika terjadi sengketa lahan, yang seharusnya turun tangan adalah aparat penegak hukum negara yang bertugas menegakkan keadilan berdasarkan hukum, bukan melindungi kepentingan salah satu pihak.
Pemerintah daerah Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara seharusnya mengambil peran mediasi yang aktif dan netral dalam kasus ini. Mereka harus memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat, memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan benar, dan melindungi hak-hak warga. Namun sejauh ini, tidak ada informasi bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik ini secara adil.
Di balik angka-angka ekonomi dan dokumen-dokumen hukum, ada dimensi manusiawi yang sering diabaikan dalam konflik agraria: dampak psikologis dan sosial pada masyarakat yang terkena dampak. Kehilangan tanah bukan hanya soal kehilangan aset ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas, Sejarah keluarga, dan rasa aman.
Bagi banyak masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah seperti Maluku Utara, tanah adalah lebih dari sekadar komoditas. Tanah adalah warisan leluhur, tempat keluarga mencari nafkah selama generasi, dan bagian dari identitas kultural. Ketika tanah itu diambil atau dirusak tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil, yang hilang bukan hanya nilai ekonomisnya, tetapi juga martabat dan hak asasi manusia.
Frustrasi yang dirasakan oleh Hamid Hasan dan keluarganya adalah representasi dari jutaan masyarakat Indonesia yang mengalami nasib serupa. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan korporasi yang memiliki sumber daya legal, finansial, dan politik yang jauh lebih besar. Mereka merasa diabaikan oleh negara yang seharusnya melindungi mereka. Mereka merasa bahwa sistem hukum tidak bekerja untuk mereka, tetapi untuk kepentingan orang-orang kaya dan berkuasa.
Ketika semua jalur formal untuk mencari keadilan tertutup atau tidak efektif, aksi-aksi seperti pemalangan dan protes menjadi pilihan terakhir. Ini bukan tindakan kriminal atau anarkis, tetapi bentuk perlawanan sipil yang sah ketika mekanisme formal gagal berfungsi. Sayangnya, tindakan ini sering kali direspon dengan kekerasan atau kriminalisasi, bukan dengan dialog dan penyelesaian yang adil.
Menyelesaikan konflik agraria seperti kasus PT Harita Nickel membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multi pihak. Tidak ada solusi sederhana atau instan, tetapi ada beberapa Langkah yang bisa dan harus diambil:
Pertama, pemerintah harus segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi yang netral dan transparan. Tim mediasi independen yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus dibentuk untuk mendengarkan semua pihak dan menemukan solusi yang adil. Proses mediasi ini harus terbuka untuk publik dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, perusahaan harus menghentikan semua aktivitas pembangunan di lahan yang disengketakan sampai status kepemilikan lahan tersebut jelas dan disepakati oleh semua pihak. Melanjutkan pembangunan di tengah sengketa hanya akan memperburuk konflik dan menunjukkan ketidakpedulian Perusahaan terhadap hak-hak masyarakat.
Ketiga, harus ada investigasi menyeluruh terhadap dugaan mafia tanah dan transaksi ilegal yang terjadi. BPN, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika perlu, harus melakukan audit terhadap semua dokumen kepemilikan lahan di lokasi proyek. Jika terbukti ada pemalsuan dokumen atau kolusi, pelaku harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
Keempat, ahli waris yang sah harus dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan terkait lahan mereka. Jika memang ada rencana untuk menggunakan lahan tersebut untuk proyek bendungan, negosiasi ganti rugi harus dilakukan secara fair, transparan, dan dengan melibatkan semua ahli waris. Besaran kompensasi harus mempertimbangkan tidak hanya nilai tanah saat ini, tetapi juga nilai ekonomi masa depan dan biaya sosial psikologis yang ditanggung oleh pemilik lahan.
Kelima, ke depannya, Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan dan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam konteks pembangunan dan investasi. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang diakui dalam standar internasional harus diterapkan secara konsisten. Masyarakat harus memiliki hak untuk menolak proyek yang merugikan mereka, dan penolakan ini harus dihormati.
Kesimpulan
Kasus sengketa lahan antara ahli waris di Halmahera Selatan dengan PT Harita Nickel adalah cermin dari masalah sistemik yang lebih besar dalam tata kelola sumber daya alam dan pembangunan di Indonesia. Ketimpangan kuasa antara korporasi dan masyarakat, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas, peran negara yang ambigu, dan maraknya praktik korupsi dan mafia tanah Adalah akar masalah yang harus ditangani secara serius.
Pembangunan dan investasi memang penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Namun pembangunan yang menginjak hak-hak dasar masyarakat, yang dilakukan dengan cara-cara tidak adil dan tidak transparan, bukanlah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang inklusif, yang melibatkan dan memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama Masyarakat yang paling terkena dampak.
Insiden saling dorong antara warga dan sekuriti perusahaan di perkebunan Halmahera Selatan mungkin tampak kecil dalam skala nasional, tetapi ia adalah simbol penting dari perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan. Bagaimana kasus ini diselesaikan akan menjadi preseden penting: apakah negara akan berpihak pada keadilan dan melindungi hak-hak rakyatnya, atau apakah korporasi akan sekali lagi diperbolehkan menindas masyarakat demi keuntungan?
Sudah saatnya kita sebagai bangsa memilih: pembangunan yang adil dan bermartabat, atau pembangunan yang menginjak-injak hak asasi manusia? Jawabannya tidak hanya akan menentukan nasib keluarga Hamid Hasan, tetapi juga akan menentukan masa depan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.
Catatan Penulis: Opini ini ditulis berdasarkan informasi dari kasus yang dipaparkan. Sebagai warga negara yang peduli pada keadilan sosial dan hak asasi manusia, penulis berharap semua pihak yang terlibat dapat menyelesaikan konflik ini dengan cara-cara yang adil, damai, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga keadilan dapat ditegakkan dan hak-hak masyarakat dapat dilindungi. (*)