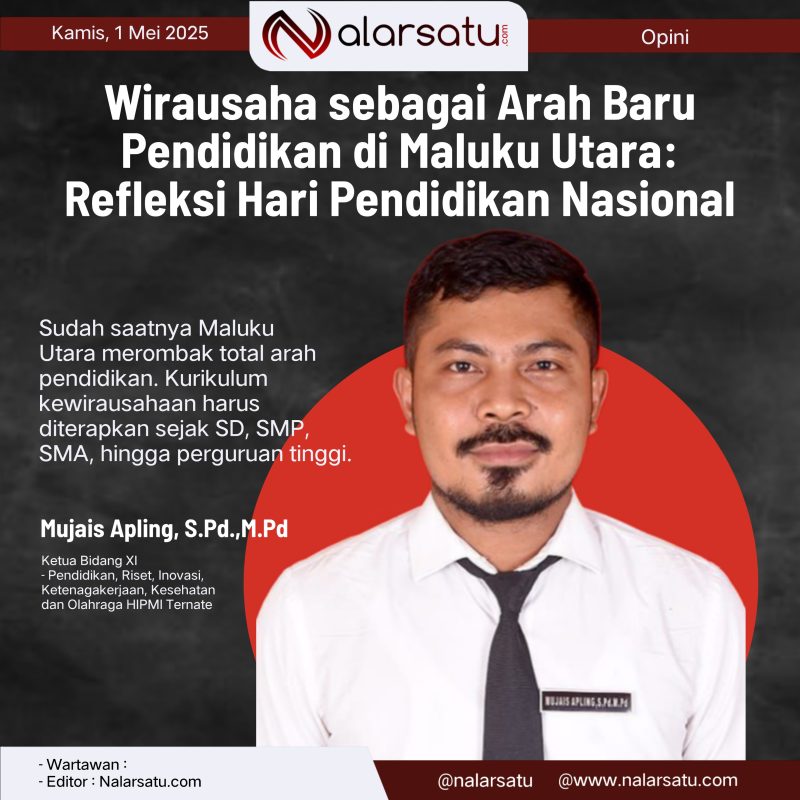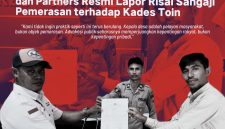Oleh: Mujais Apling, S.Pd.,M.Pd (Ketua Bidang XI – Pendidikan, Riset, Inovasi, Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Olahraga HIPMI Ternate)
Tanggal 2 Mei selalu hadir sebagai seremoni nasional, dengan upacara, pidato, dan formalitas yang sekilas tampak meriah. Namun, jauh dari gegap gempita seremoni itu, realitas pendidikan di Maluku Utara justru makin menyedihkan. Setiap tahun kita mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, namun lupa untuk menelusuri kembali semangat dan kritik tajam yang dulu ia lontarkan terhadap sistem pendidikan kolonial. Kita sibuk dengan seremoni, tapi malas berbenah dalam substansi. Di tengah ketimpangan, stagnasi kurikulum, dan kemiskinan guru, pendidikan kita nyaris tidak mengalami pembaruan berarti. Kita terus mengulang sistem pendidikan lama yang hanya mencetak barisan panjang pencari kerja, terutama pencari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seolah-olah itulah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan.
Masalahnya bukan sekadar orientasi yang keliru, tetapi juga kesadaran yang tumpul. Pendidikan di Maluku Utara telah lama dibiarkan berjalan dalam ruang hampa inovasi. Sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, peserta didik digiring untuk patuh pada doktrin formal, rajin sekolah, tamat, lalu cari kerja. Tak heran jika mayoritas pelajar dan mahasiswa di provinsi ini bermimpi menjadi PNS. Bahkan orang tua pun menganggap anak yang sukses adalah anak yang bisa “masuk kerja negeri”. Ini bukan salah anak-anak muda, bukan pula salah para guru sepenuhnya. Ini adalah hasil dari sistem pendidikan yang gagal membaca perubahan zaman dan tidak memiliki keberanian untuk mengubah orientasi secara radikal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, peluang kesejahteraan terbesar justru bukan di jalur ASN. Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang melimpah: hasil laut, pertanian, kehutanan, hingga tambang. Tapi kekayaan itu tidak otomatis mengangkat rakyatnya dari kemiskinan. Mengapa? Karena kita tidak mendidik generasi muda untuk menjadi pelaku ekonomi mandiri. Kita lebih sibuk mencetak ijazah daripada menciptakan kemandirian. Kita lebih bangga pada kelulusan daripada kemampuan menghidupi diri sendiri. Padahal, akar dari kesejahteraan adalah kemandirian ekonomi. Dan itu hanya bisa dicapai jika pendidikan sejak dini diarahkan untuk melahirkan wirausahawan, bukan sekadar pegawai.
Sudah saatnya Maluku Utara merombak total arah pendidikan. Kurikulum kewirausahaan harus diterapkan sejak SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ini bukan sekadar tambahan pelajaran formal seperti yang sering dilakukan pemerintah, tetapi harus menjadi jiwa dari seluruh proses pendidikan. Anak SD diajak mengenal nilai uang, belajar menabung, dan diajak berdagang secara sederhana dalam kegiatan belajar. Siswa SMP mulai didorong membuat produk kecil dari potensi sekitar. Di tingkat SMA dan perguruan tinggi, siswa dan mahasiswa harus didampingi membuat usaha nyata yang bisa dikembangkan. Ini bukan mimpi kosong. Banyak daerah di Indonesia bahkan di negara-negara berkembang telah memulainya, dan berhasil mengangkat kesejahteraan rakyatnya dari fondasi pendidikan berbasis wirausaha.
Sayangnya, di Maluku Utara, konsep kewirausahaan masih dianggap pelengkap. Paling banter hanya berupa satu mata pelajaran yang tidak pernah menyentuh praktik. Atau seminar musiman yang tidak ditindaklanjuti. Padahal, akar dari wirausaha bukan terletak pada pengetahuan teoretik, melainkan pengalaman konkret dan keberanian mencoba. Sekolah dan kampus kita terlalu takut gagal, terlalu banyak birokrasi, dan terlalu sedikit ruang untuk eksperimen kreatif. Di sisi lain, lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki potensi untuk membuka jalan baru malah ikut terseret dalam arus formalitas, sibuk mengurus akreditasi, administrasi, dan pelaporan yang kering makna.
Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kondisi tenaga pendidik yang makin hari makin terpinggirkan. Di pelosok-pelosok Halmahera, Obi, Bacan, Morotai dan Makian, masih banyak guru honorer yang digaji tak sampai setengah dari upah minimum. Mereka mengajar dengan semangat setengah mati, tanpa jaminan kesehatan, tanpa pelatihan memadai, dan tanpa penghargaan yang layak. Pemerintah daerah masih memandang guru sebagai pelengkap sistem, bukan sebagai ujung tombak perubahan. Lalu bagaimana kita berharap perubahan terjadi jika yang mengajar sendiri hidup dalam ketidakpastian?
Fasilitas pendidikan juga menjadi sorotan. Di banyak sekolah, bangunan sudah rusak, peralatan laboratorium tidak ada, buku-buku usang, dan akses internet terbatas. Kita berbicara tentang revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan, dan ekonomi digital, tetapi siswa di desa-desa masih harus belajar di bangku reyot dengan papan tulis penuh coretan. Pendidikan macam apa yang bisa tumbuh dari ketimpangan seperti ini? Sistem pendidikan kita masih diskriminatif terhadap wilayah, memperkuat jurang antara kota dan desa, antara sekolah unggulan dan sekolah seadanya. Wirausaha tidak bisa lahir dari ketimpangan seperti ini. Pendidikan untuk kemandirian membutuhkan infrastruktur yang adil dan akses yang merata.
Tanggal 2 Mei seharusnya tidak menjadi ajang perayaan belaka. Ini bukan soal mengenang sejarah masa lalu. Ini soal keberanian untuk mengubah masa depan. Refleksi pendidikan harus dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar: pendidikan untuk siapa dan untuk apa? Jika jawabannya adalah untuk rakyat, maka pendidikan harus mengakar pada realitas rakyat. Jika jawabannya adalah untuk kesejahteraan, maka pendidikan harus menjadi alat untuk membebaskan rakyat dari ketergantungan ekonomi. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi mesin pencetak pegawai. Ia harus menjadi ruang tumbuh bagi kreativitas, keberanian, dan kemandirian.
Pemerintah daerah tidak boleh lagi berpikir normatif. Ini waktunya berpikir transformatif. Sistem pendidikan harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Sekolah dan kampus tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan dunia usaha, pasar lokal, dan teknologi digital. Koperasi siswa, inkubator bisnis pelajar, pelatihan produksi lokal, dan platform pemasaran digital harus menjadi bagian dari keseharian sekolah. Guru tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi menjadi mentor kewirausahaan. Mahasiswa tidak hanya menulis skripsi, tetapi mendirikan usaha riil. Lulusan tidak hanya mencari kerja, tetapi membuka lapangan kerja bagi orang lain.
Jika pendidikan terus dijalankan seperti sekarang, kita hanya mencetak generasi yang gelisah. Mereka sekolah tinggi, tetapi tak tahu harus ke mana. Mereka punya ijazah, tapi tidak punya daya saing. Mereka cerdas di kelas, tapi lumpuh di pasar. Pendidikan seperti ini hanya melahirkan frustrasi kolektif yang suatu saat bisa meledak dalam bentuk apatisme sosial atau konflik struktural. Maka dari itu, perubahan harus dimulai sekarang. Hari Pendidikan Nasional tidak boleh lagi dipenuhi dengan jargon usang dan seremonial kosong. Ia harus menjadi hari kesadaran baru. Kesadaran bahwa pendidikan harus bergeser dari zona nyaman menuju zona perjuangan. Dari pencetak buruh menjadi pencipta usaha. Dari orientasi negeri menjadi orientasi mandiri.
Maluku Utara punya semua syarat untuk menjadi model pendidikan wirausaha di Indonesia. Potensi lokal melimpah. Budaya gotong royong masih kuat. Semangat anak muda masih menyala. Yang dibutuhkan hanya satu: keberanian politik. Keberanian untuk melawan sistem lama yang mandul. Keberanian untuk menyusun kurikulum baru yang membebaskan. Keberanian untuk membela guru, memperbaiki sekolah, dan membiayai perubahan dengan sungguh-sungguh.
Dan itu semua hanya bisa terjadi jika kita, rakyat Maluku Utara, mulai bersuara lebih keras. Mulai bertanya lebih tajam. Mulai mendesak lebih gigih. Karena pendidikan bukan urusan pejabat semata. Pendidikan adalah hak kolektif yang menentukan arah sejarah kita. Kita harus merebut kembali makna pendidikan, menjadikannya alat pembebasan, bukan alat penjinakan.
Jika kita masih percaya bahwa pendidikan bisa mengubah nasib, maka kita harus berani mengubah wajah pendidikan kita sendiri. Dan perubahan itu harus dimulai hari ini. Bukan besok. Bukan tahun depan. Tapi sekarang juga. (*)